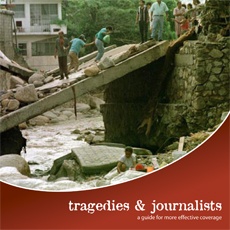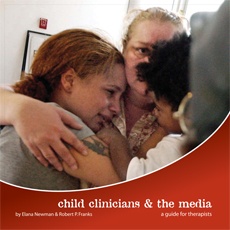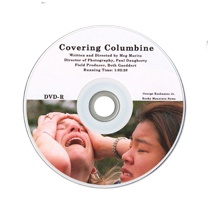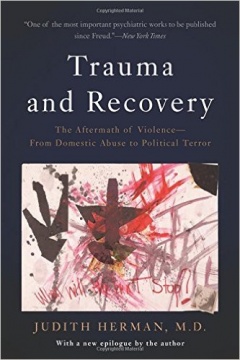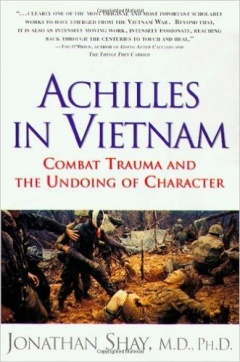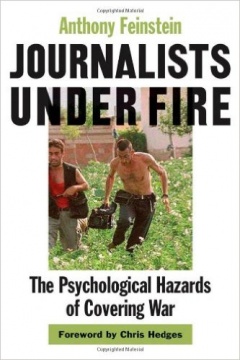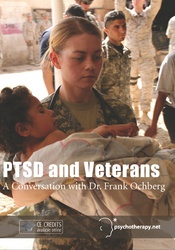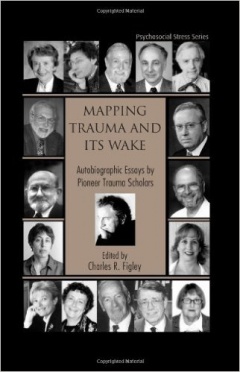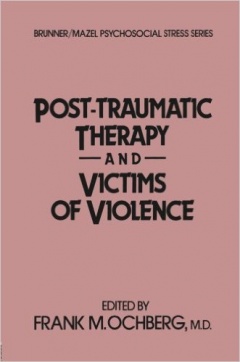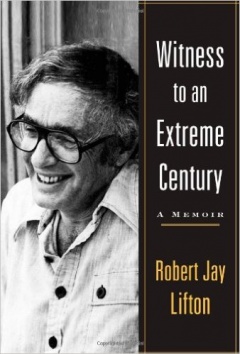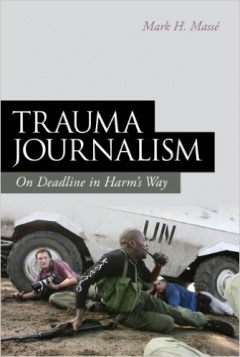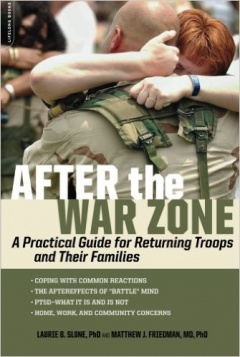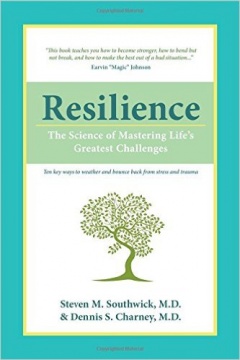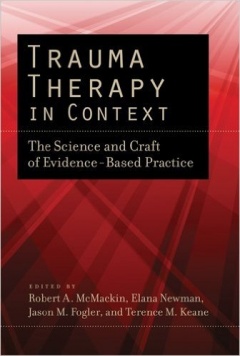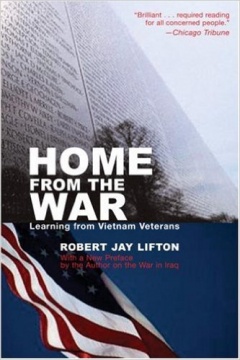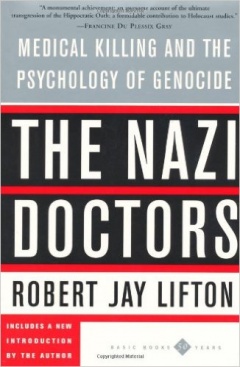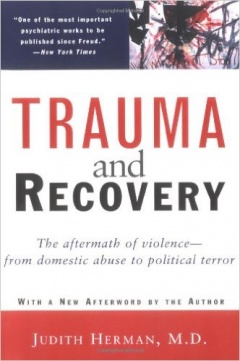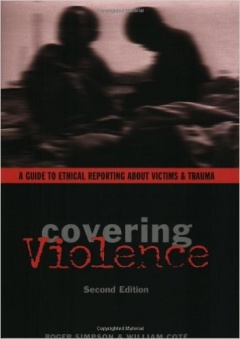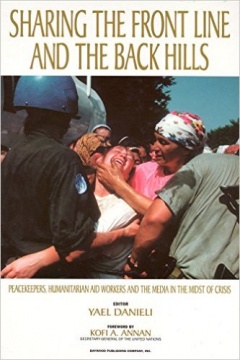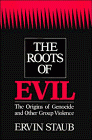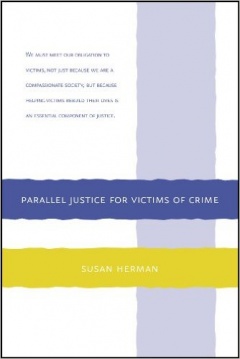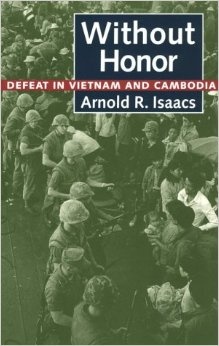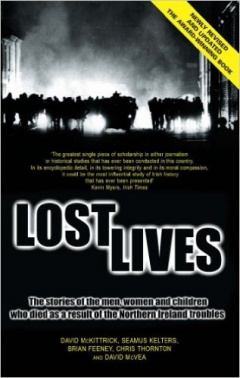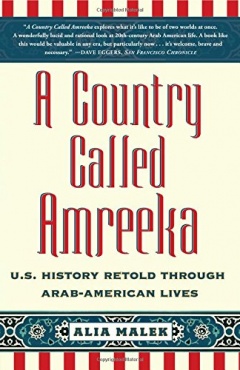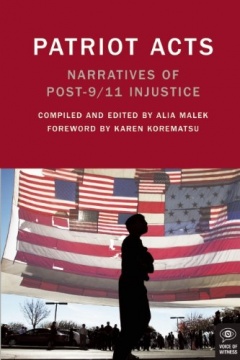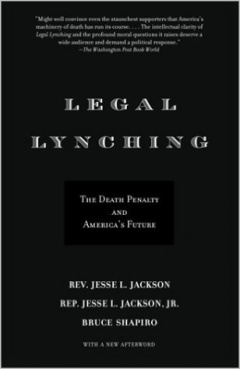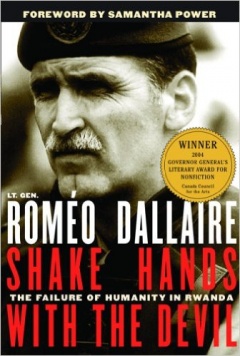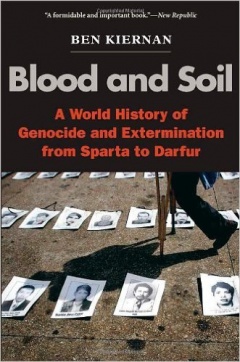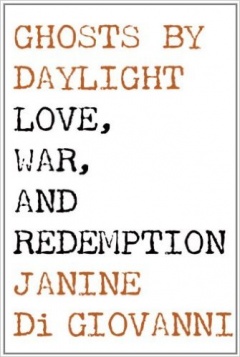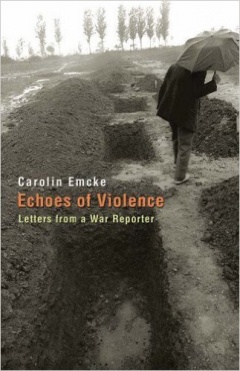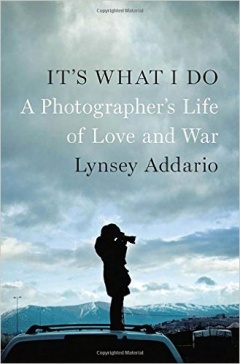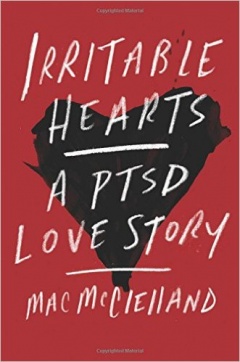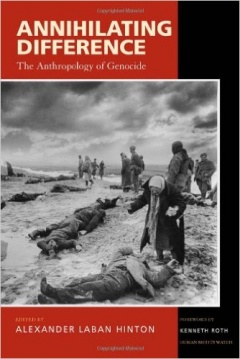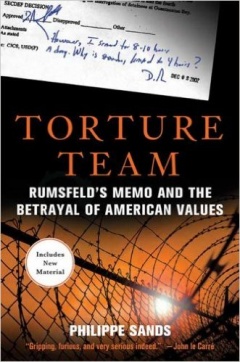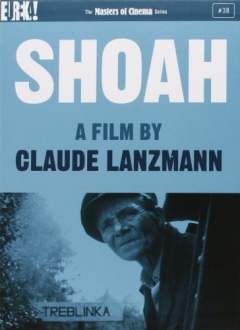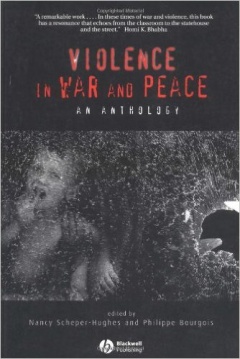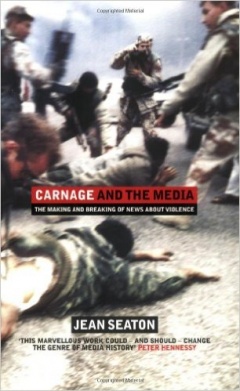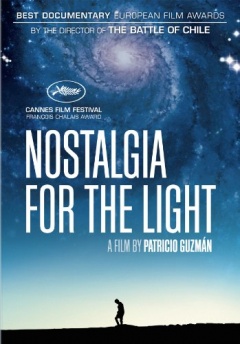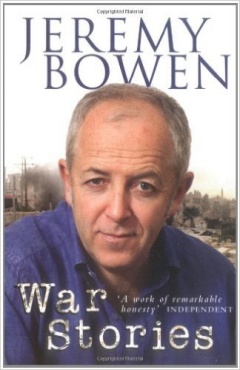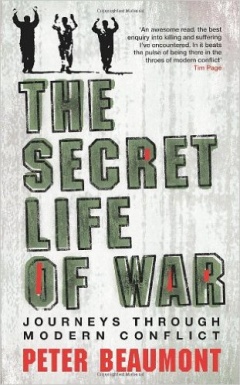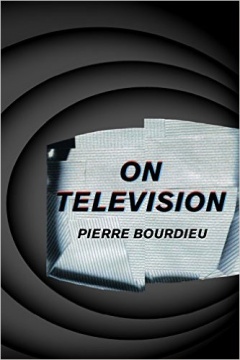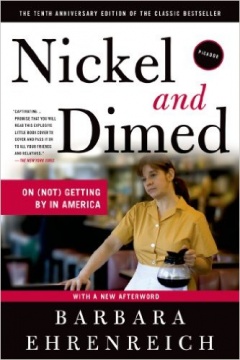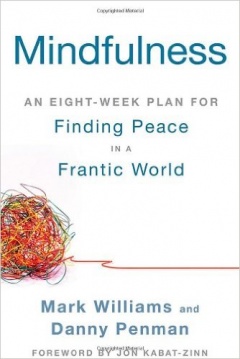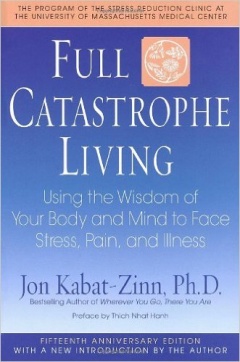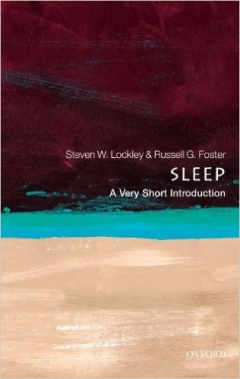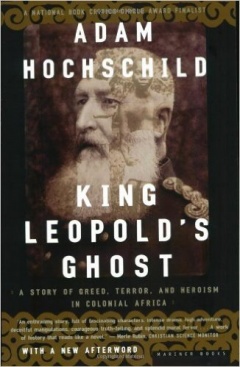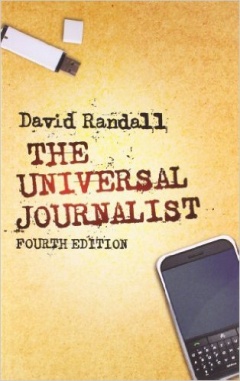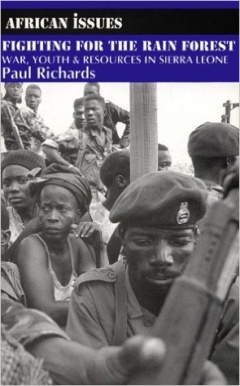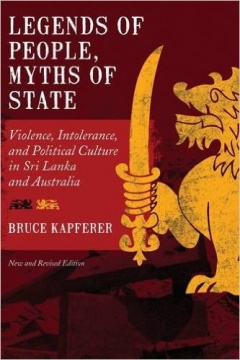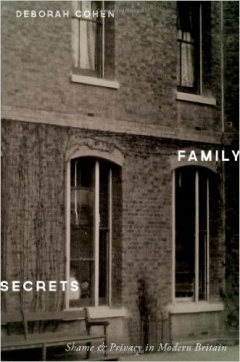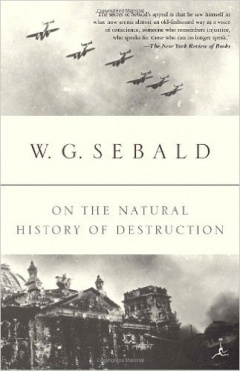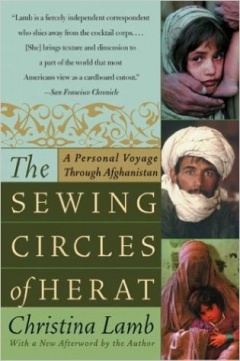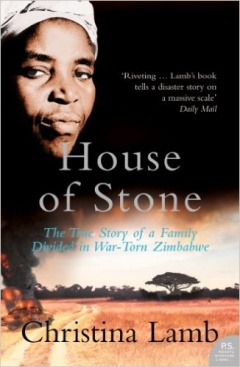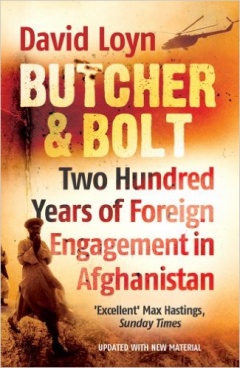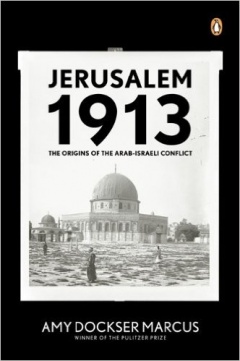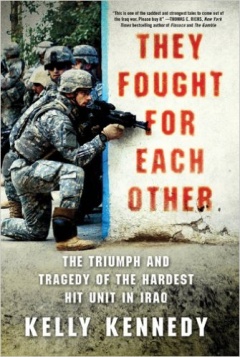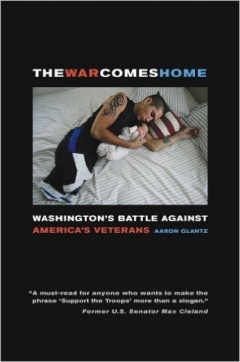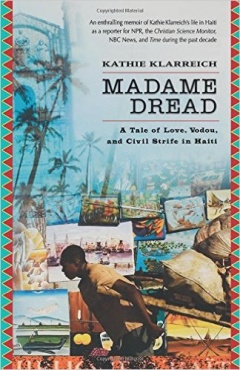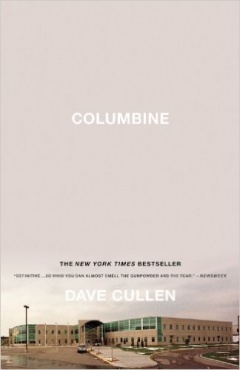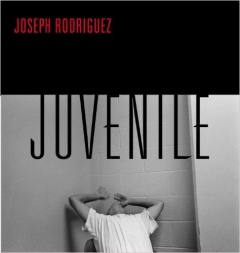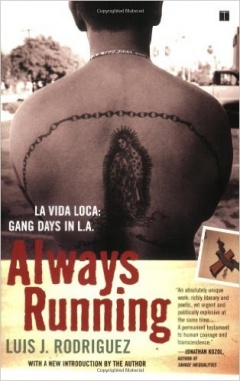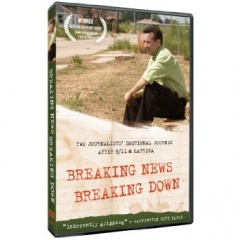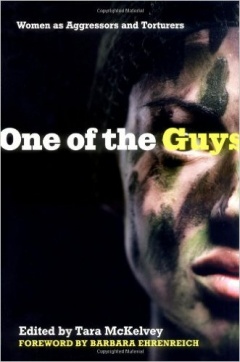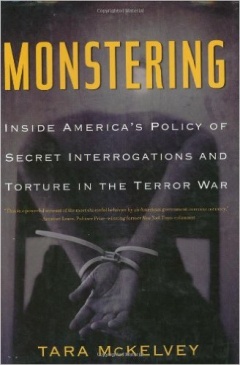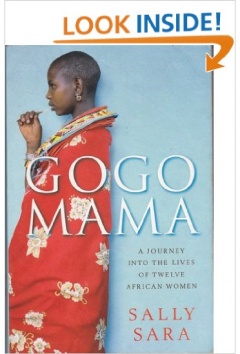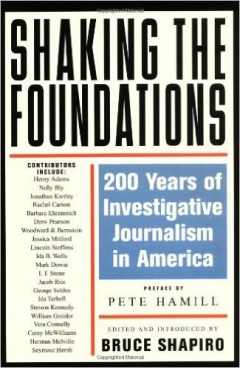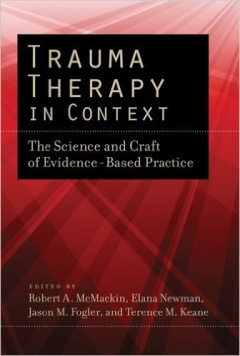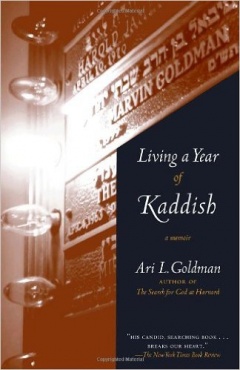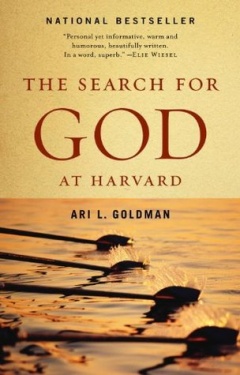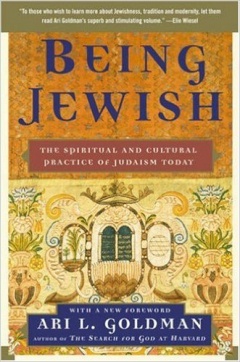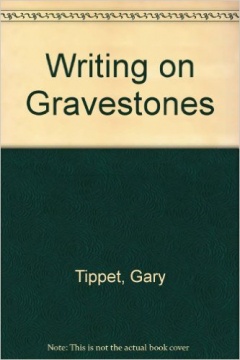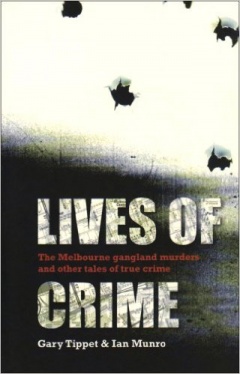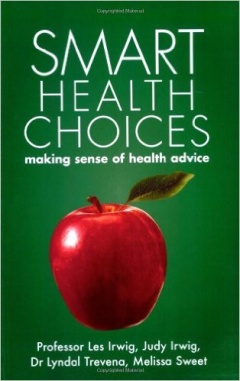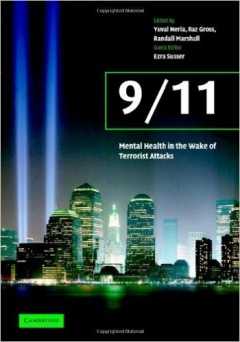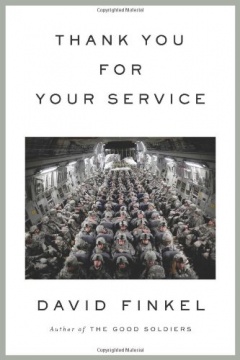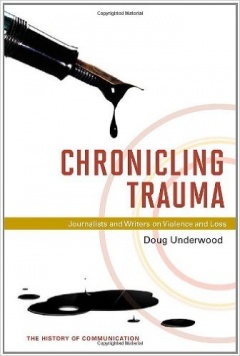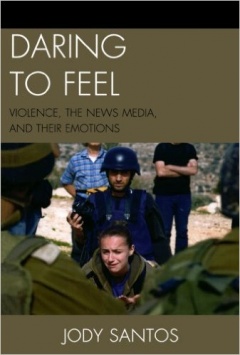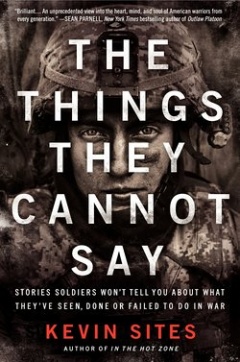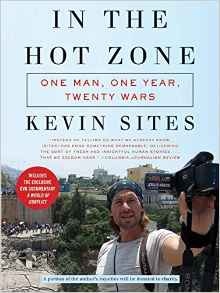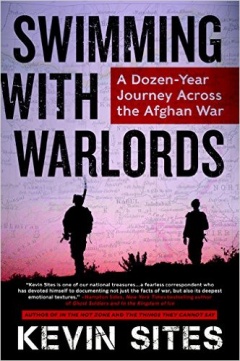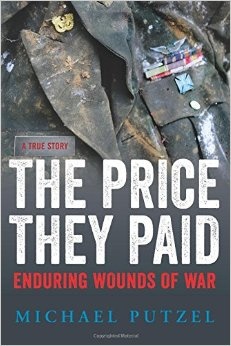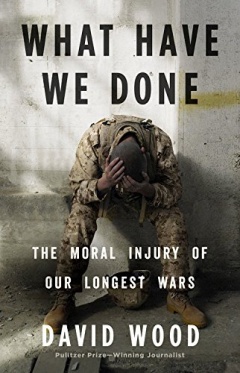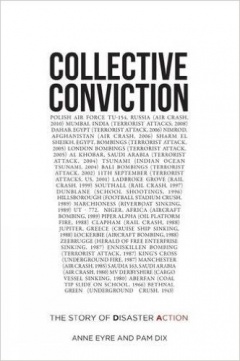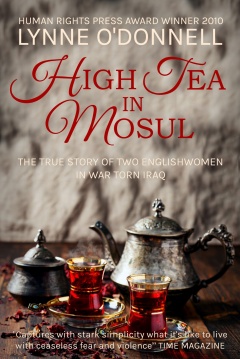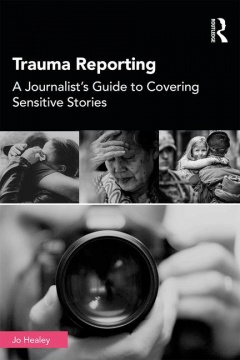Suka Dan Duka Menjadi Wartawan Di Perbatasan Indonesia Dan Timor Leste
Peter Tukan was a participant at a three-month intensive training program facilitated by RMIT International (Melbourne, Australia) which was funded by a bilateral program between Indonesia and the Australian Government (IASTP). The Dart Centre Australasia took responsibility for the trauma and journalism component of the course, which ran over nearly three weeks.
Dart Australasia Director Cait McMahon asked Tukan to introduce himself and tell something of his experiences reporting from both inside East Timor prior to its independence, and living in the border region (on the Indonesian side) post independence. This is Peter Tukan’s story.
(The views expressed in this story are those of the author only.)
Saya mengeluti dunia jurnalistik dengan menjadi wartawan media cetak sejak tahun 1984, ketika masih sebagai mahasiswa pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik/Seminari Tinggi Santo Paulus, Ledalero, Maumere, Flores.Antara tahun 1984-1989, saya menjadi koresponden Majalah Mingguan HIDUP Katolik yang diterbitkan di Jakarta dan Tabloid Mingguan terbitan Ende, Flores selain menjadi staf redaksi “VOX”- Majalah Mahasiswa Kampus Sekolah Tinggi Filsafat, Ledalero. Tahun 1989 saya mulai mengasuh bulletin “Keluarga” yang diterbitkan Komisi Keluarga Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Jakarta dan tahun 1990 -1992 menjadi wartawan Mingguan HIDUP di Jakarta. Februari 1992 saya meninggalkan Jakarta menuju Dili, Timor Timur untuk selanjutnya bekerja di Harian “Suara Timor Timur” di Dili sebagai redaktur hingga 1996 dan sejak April 1996 saya bergabung dengan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Biro Dili sampai sekarang. Selain menjadi wartawan ANTARA saya pun masih menjadi koresponden Kantor Berita Katolik Asia (Union of Catholic News-UCAN) yang berkantor pusat di Bangkok,Thailand.
Pada tahun 1999, setelah Referendum di Timor Leste, saya ditugaskan menjadi wartawan ANTARA di Perwakilan Atambua, Nusa Tenggara Timur, wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste.
Saya menikah dengan Lucina Oliva Seli Seng pada 30 Agustus 1995 di Maumere. Kami telah dikaruniai seorang anak bernama Carlos Ximenes Henriques yang lahir di Dili,Timor Timur pada 19 Juni 1996 dan dibaptis oleh Uskup Dioses Dili, Dom Carlos Filipe Ximenes Belo, SDB pada 8 Agustus 1996. Istriku adalah seorang guru pada Sekolah Perawat Kesehatan Akademi Keperawatan (Akper) di Atambua, ibukota Kabupaten Belu.
Pada tahun 1995-1996, saya menulis dan menjadi editor buku tentang Timor Timur dengan judul: “Suara Kaum Tak Bersuara” dan “Demi Keadilan dan Perdamaian”. Buku ini diterbitkan dalam rangka penganugerahan hadiah Nobel Perdamaian kepada Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo,SDB.
Selama bekerja di Timor Timur, saya dipercaya Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo sebagai Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian (Justice and Peace) sebuah lembaga Gereja Keuskupan Dili yang bertugas memberikan pendampingan atau advokasi kepada masyarakat Timor Timur di bidang penegakkan hak asasi manusia, keadilan dan perdamaian.
Ketika mulai bekerja di Atambua (September 1999), saya mendapat kepercayaan dari Uskup Dioses Atambua, Mgr Anton Pain Ratu,SVD untuk menjadi anggota Komisi Komunikasi Sosial (Komsos) Keuskupan Atambua.
Pada tahun 2001, saya menerima penghargaan dari UCAN sebagai wartawan penulis feature human interest terbaik. Tulisan itu tentang kisah kedatangan dan penugasan United Nation Peace Keeping Forces (UNPKF) ke Timor Leste yang dipimpin Australia untuk memelihara perdamaian di Timor Leste pasca Referendum 30 Agustus 1999.
Saya telah mengikuti beberapa training jurnalistik antara lain tentang Jurnalisme Damai (Peace Journalism) yang diselenggarakan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dan pelatihan wartawan di daerah konflik yang diselenggarakan atas kerjasama ICRC dan Palang Merah Indonesia (PMI) di Jakarta.
Pengalaman di daerah konflik Timor Leste
Selama bertugas di Timor Timur (1992-1999), saya menilai wilayah ini merupakan daerah konflik yang sangat spesifik karena telah terjadi konflik antar kelompok masyarakat Timor Timur sendiri yakni kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Timor Leste dengan kelompok yang mendukung integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Masyarakat di sini terpecah-belah dalam dua kelompok besar itu. Selain itu terjadi konflik bersenjata antara para pejuang kemerdekaan Timor Leste dengan militer Indonesia yang berada di wilayah ini sejak 1975 hingga 1999.
Selain terjadi konflik bersenjata juga telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang banyak dilakukan oleh militer. Di dalam situasi konflik seperti ini, kelompok masyarakat yang paling menderita dan mengalami trauma yang paling mendalam adalah kaum perempuan dan anak-anak.
Selama bertugas di Timor Timur, saya bersama keluarga sering mengalami ancaman fisik oleh orang-orang yang tidak dikenal. Saya pernah dua kali dipukul oleh kelompok orang tidak dikenal ketika sedang dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor dari kantor redaksi Harian Suara Timor Timur ke rumah yang berjarak sekitar empat kilometer. Mereka memakai penutup muka ala ninja dan menghentikan kendaraanku dan langsung menampar beberapa kali. Saya terjatuh dari sepeda motor dan mereka pun lari meninggalkanku. Pengalaman lain, saya diancam dibunuh oleh seorang yang tidak dikenal. Dia menampar pipiku lalu meninggalkan aku sendirian. Masih beruntung karena dia tidak menggunakan senjata tajam atau senjata api untuk menghabisi nyawaku.
Saya menyadari bahwa ancaman fisik itu justeru dilakukan oleh pihak tertentu yang merasa tulisanku pada media sangat merugikan mereka. Saya tahu kelompok mana yang melakukan hal ini namun pada kesempatan ini tidak saya sebutkan nama kelompok atau oknum itu.Cukup saya sendiri yang mengetahuinya.Hal ini pun tidak pernah saya sampaikan kepada istriku agar dia tidak mengalami trauma.Istriku tahu kalau saya diancam dan pernah dipukul namun sampai hari ini dia tidak tahu siapa atau kelompok apa yang melakukan hal tersebut.Cukuplah saya sendiri yang mengetahuinya.
Pada masa persiapan referendum tepatnya Mei 1999, saya diancam lagi oleh salah seorang Pemimpin milisi pro Integrasi. Dia bersama anak buahnya berencana menculik aku untuk dihabisi nyawa. Namun, seorang rekanku di dalam kelompok pro-integrasi itu masih berusaha menghalangi rencana tersebut sehingga aku selamat dari ancaman kematian itu. Mereka tidak puas atas sikapku yang netral dan tidak mendukung perjuangan mereka mempertahankan keutuhan Timor Timur dengan Indonesia.
Mereka tahu kalau saya sangat dekat dan terus bekerjasama dengan Gereja Katolik yang ketika itu diketahui sangat mendukung kemerdekaan Timor Leste. Kedekatan dan kerjasama dengan lembaga Gereja diidentikkan dengan “mendukung kemerdekaan Timor Leste”. Padahal, saya sendiri memiliki prinsip kerja sendiri sebagai wartawan. Bagiku, persoalan politik kemerdekaan Timor Leste atau integrasi Timor Timur dengan Indonesia bukanlah urusanku. Saya tidak berurusan dan tidak peduli dengan masalah itu. Saya hanya peduli pada tugasku memberitakan berbagai peristiwa kehidupan masyarakat setempat berlandaskan etika jurnalistik tanpa sedikitpun terpengaruh dengan misi politik dari setiap kelompok yang bertikai.
Pengalaman lain yang tidak pernah kulupakan adalah tindakan sesama rekan wartawan yang melaporkan kepada pimpinanku bahwa saya adalah orang yang mendukung dan berjuang untuk kemerdekaan Timor Leste. Laporan itui sangatlah berbahaya bagi masa depan kehidupan dan keluarga. Saya bisa saja terancam dipecat karena sebagai warga negara Indonesia dilaporkan ikut mendukung perjuangan kemerdekaan Timor Leste.
Namun, ternyata laporan tersebut tidak dihiraukan oleh pimpinan tertinggi tempat saya bekerja sehingga kecemasanku (pada saat itu) akan kehilangan mata pencaharian segera berakhir. Pimpinan tertinggi tempat saya bekerja mengetahui dan memahami secara baik semua pekerjaan yang kulakukan selama berada di Timor Timur. Pengalaman pahit itu masih juga membekas dalam batinku.
Selain trauma kekerasan ketika menjalankan tugas jurnalistik, saya juga punya pengalaman traumatic lainnya yakni pada menjelang referendum Timor Timur, saya harus mengungsikan istri dan anak ke Pulau Flores. Pada April 1999, istri dan anakku meninggalkan Dili,ibukota Provinsi Timor Timur. Mereka hanya membawa pakaian seadanya saja dalam perjalanan itu dengan menumpang kapal laut dari Dili ke Maumere, Flores.
Istri dan anakku membawa pakaian secukupnya ke Flores karena akan kembali lagi ke Timor Timur apalagi propaganda ketika itu adalah pihak pro-integrasi akan memenangkan Referendum pada 30 Agustus 1999. Mayoritas rakyat Timor Timur akan memilih tetap berintegrasi dengan Indonesia. Namun ternyata, dugaan itu tidak benar karena pada referendum itu, kelompok pro- kemerdekaan Timor Leste menang yang berarti rakyat Timor Leste memperoleh kemerdekaan dan Indonesia harus keluar dari wilayah ini.
Kemenangan rakyat Timor Timur pada referendum untuk menjadi sebuah negara merdeka berdampak pada pengungsian ratusan ribu rakyat di Timor Timur ke wilayah Timor bagian barat, Nusa Tenggara Timur..
Saya bersama istri dan anak harus kehilangan rumah di Dili yang kami beli secara mencicil pada Bank Tabungan Negara (BTN). Rumah seharga Rp35 juta terpaksa ditinggalkan karena Timor Leste sudah merdeka. Begitu pula semua perabot rumah tangga ditinggalkan di Dili karena situasi keamanan di kota itu sudah tidak dapat dikendalikan lagi.Kami tidak memiliki kesempatan lagi untuk menyelamatkan barang-barang yang berada di dalam rumah tersebut. Semua hasil jerih-payah bekerja selama bertahun-tahun berupa rumah dan segala isinya terpaksa ditinggalkan untuk dirampok oleh orang-orang yang tidak dikenal pada tragedi berdarah pasca pengumuman hasil Referendum pada 4 September 1999.
Kami terpaksa mengungsi ke Atambua tanpa memiliki pakaian yang cukup dan perabot rumah tangga. Kami harus memulai hidup baru sambil tetap melaksanakan tugas jurnalistik secara profesional.
Pada April 2005 yang lalu, ketika saya bertugas di Dili dalam rangka kunjungan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono ke Timor Leste, saya masih menyempatkan diri melihat rumah yang kami tinggalkan pada 7 September 1999 namun ternyata rumah itu sudah ditempati oleh warga masyarakat Timor Leste. Ketika mereka mengetahui bahwa rumah tersebut milikku, maka mereka mengusir saya dengan mengatakan, “Indonesia sudah kalah pada referendum sehingga semua milik orang Indonesia menjadi milik orang Timor Leste. Kamu tidak lagi berhak atas rumah ini”.
Saya pun tidak membantah atau berkeberatan atas pernyataan tersebut karena saya menyadari bahwa lebih baik rumahku yang masih utuh itu diberikan kepada orang Timor Leste secara gratis dari pada dipersoalkan kepemilikannya yang akan berakibat pada konflik yang berkepanjangan.
Saya masih ingat bahwa setelah saya mengungsi dari Timor Timur pada 7 September 1999 ke Atambua, wilayah perbatasan, saya masih tetap melaksanakan tugas jurnalistik seperti biasa. Berita yang saya tulis dari perbatasan tentang pengungsian ratusan ribu rakyat tidak berdosa.
Namun pada 12 September 1999, saya mendapat penugasan untuk kembali memasuki wilayah Timor Leste dalam rangka kedatangan UNPKF ke wilayah itu untuk menjaga dan memulihkan perdamaian di Timor Timur. Saya pun kembali ke Timor Timur dengan menumpang mobil yang memasuki wilayah itu. Saya bertugas di Dili yang sedang dilanda kebakaran hebat itu sampai kedatangan UNPKF pimpinan Australia. UNPKF tiba di Dili pada 20 September dipimpin Mayjen Peter Cosgrove. Sejak itu Timor Timur berada di bawah pengawasan UNPKF dan Panglima Darurat Militer Indonesia yang dipimpin Mayjen TNI Kiki Syahnakri.
Pada 25 September 1999, saya kembali lagi ke Atambua bersama para pengungsi namun pada Oktober 1999 banyak pengungsi (berkat bantuan UNHCR) kembali lagi ke Timor Timur. UNHCR memfasilitasi kepulangan para pengungsi dari Timor Barat ke Timor Leste melalui perjalanan darat dengan menggunakan banyak mobil truk dan juga melalui perjalanan laut dengan menggunakan kapal ferry yang berlabuh di dermaga Atapupu, sekitar 25 Km arah Utara kota Atambua.
Pada kesempatan repatriasi itu, saya kembali lagi memasuki wilayah Timor Leste. Saya memanfaatkan pelayaran kapal ferry yang membawa pulang pengungsi Timor Timur. Ketika berada di Dili, saya menerima sepucuk surat dari Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo yang memberikan rekomendasi kepadaku untuk melakukan peliputan di Timor Timur. Surat tersebut ditandatangani pula oleh Panglima UNPKF,Mayjen Peter Cosgrove.
Berdasarkan surat rekomendasi itulah maka saya bebas memasuki wilayah Timor Leste dan bebas pula melakukan peliputan di wilayah ini. Saya banyak dibantu oleh para anggota UNPKF terutama keamanan diriku selama melakukan tugas jurnalistik di tengah masyarakat Timor Timur yang ketika itu sangat marah terhadap tindakan pembakaran kota Dili oleh kelompok tertentu.
Saya melakukan tugas jurnalistik di Dili selama tiga hari dan setelah itu kembali lagi ke Atambua (dengan menumpang kapal Ferry) untuk menulis berita di Atambua. Dalam perjalanan pulang ke Atambua, saya membawa titipan uang dari banyak warga masyarakat Timor Timur untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, garam, korek api, gula pasir dan sebagainya.
Setelah berbelanja di Atambua, saya membawa lagi hasil belanjaan itu ke Dili dengan menumpang kapal ferry yang secara rutin membawa pulang pengungsi Timor Timur ke tanah kelahiran mereka. Setibanya di Dili, semua barang pesanan warga Timor Timur itu diberikan kepada mereka karena pada waktu itu Dili bagaikan kota mati yang tidak memiliki makanan dan kebutuhan sehari-hari kecuali mereka mendapat bantuan darurat dari UNHCR dan berbagai NGO yang sudah mulai bertugas di wilayah itu pasca kerusuhan dan pembakaran kota Dili.
Saya mengalami banyak kesulitan ketika membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari yang saya beli dari Atambua ke Dili. Barang-barang titipan masyarakat Timor Leste itu diperiksa di dermaga Atapupu oleh oknum tertentu. Banyak di antaranya seperti beras, gula pasir dan terigu ditahan di pelabuhan itu karena menurut mereka, kita tidak perlu membantu rakyat Timor Timur karena mereka sudah memilih merdeka, lepas dari Indonesia. Saya sendiri diancam oleh oknum tertentu karena diketahui membawa bantuan untuk rakyat di Timor Timur. Namun berkat bantuan staf UNHCR yang bertugas di pelabuhan Atapupu itu, banyak barang titipan rakyat Timor Leste itu berhasil diangkut ke Dili bersamaan dengan kembalinya para pengungsi ke tanah kelahiran mereka.
Ketika berada di atas kapal ferry menuju Dili, saya merasa sangat aman karena mengantongi surat rekomendasi dari Uskup Belo yang disetujui oleh panglima UNPKF Mayjen Peter Cosgrove.
Pada masa yang sangat sulit dan mencekam itu, saya tetap menjalankan dua tugas mulia dari Atambua ke Dili atau sebaliknya dari Dili ke Atambua melalui pelayaran kapal ferry yaitu tugas jurnalistik meliput repatriasi pengungsi Timor Timur sekaligus melakukan tugas kemanusiaan yakni membelanjakan kebutuhan sehari-hari warga Timor Timur di Atambua untuk selanjutnya dibawa ke Dili.
Kegiatan membantu warga Timor Timur membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari di Atambua dan membawa kembali ke Dili saya lakukan sampai Desember 1999. Dan memasuki tahun 2000, kegiatan ini berakhir karena masyarakat Timor Timur sudah mendapat banyak bantuan sandang dan pangan dari berbagai lembaga kemanusiaan internasional.
Sampai hari ini, begitu banyak warga Timor Leste tidak pernah melupakan apa yang telah saya lakukan untuk mereka – terutama membelanjakan kebutuhan pangan pada masa darurat di Atambua dan membawanya ke Dili melalui pelayaran kapal ferry.
Saya pun masih ingat. Ketika oknum tertentu menahan barang-barang titipan warga Timor Timur seperti beras, terigu, minyak goreng di pelabuhan Atapupu, saya menjadi sangat takut bukan takut kepada oknum yang menahan barang-barang tersebut melainkan takut pada warga Timor Timur yang telah menitipkan uang mereka untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Saya takut mereka menuduh saya membohongi mereka karena barang-barang yang mereka butuhkan tidak dibawa ke Dili. Ternyata barang-barang itu ditahan di pelabuhan Atapupu.
Untuk itu, saya sering harus menggunakan uang pribadi untuk membeli kembali barang-barang kebutuhan yang sudah ditahan atau diambil oknum tertentu itu untuk selanjutnya dibawa ke Dili.Apa yang saya lakukan ini hanya semata-mata untuk menjaga kepercayaan warga Timor Timur terhadap diriku. Saya tahu, walaupun saya mengatakan barang-barang kalian yang sudah kubeli ditahan/diambil oknum tertentu di pelabuhan Atapupu, mereka akan tetap tidak percaya karena mereka sendiri tidak melihat apa yang terjadi di pelabuhan itu. Apalagi pada waktu itu mereka sedang berada dalam keadaan sangat menderita akibat kehilangan harta benda pasca Referendum. Dalam situasi seperti ini, mereka sangat mudah tersinggung dan mencurigai setiap orang Indonesia yang memasuki wilayah Timor Leste bersama kembalinya para pengungsi.
Di dalam situasi seperti ini satu hal yang sangat menyenangkan adalah istriku tetap mamahami apa yang sedang saya lakukan itu sehingga walaupun cukup banyak uang dari gajiku dan gajinya digunakan untuk membeli kembali barang-barang kebutuhan warga Timor Timur untuk selanjutnya dibawa ke Dili, dia tetap bersikap sabar dan tidak melakukan protes. Dia tahu, lebih baik kami berkorban mengeluarkan uang pribadi untuk membeli kebutuhan warga Dili yang diambil oknum tertentu di pelabuhan Atapupu daripada kami kehilangan kepercayaan warga Timor Timur yang telah menitipkan uang mereka kepadaku untuk membelanjakan kebutuhan rumah tangga mereka.
Kami bukanlah keluarga kaya. Tetapi apa yang kami miliki di dalam kesederhanaan hidup itulah yang kami berikan kepada sesama dengan tulus hati. Inilah yang kita sebut:”Orang miskin membantu orang susah”.
Saya juga memiliki pengalaman khusus dengan rekan-rekan wartawan selama bertugas di Timor Timur khususnya pada menjelang Referendum di wilayah itu. Ketika itu begitu banyak wartawan berdatangan dari berbagai negara.Mereka menulis banyak berita tentang Timor Timur namun tidak sedikit berita itu menjadi bias. Bias berita tentang Timor Timur berdampak pada terjadinya konflik baru atau semakin menambah konflik antarwarga masyarakat Timor Timur.
Hal ini terjadi, pertama-tama karena banyak sekali wartawan yang meliput di Timor Timur ketika itu tidak memahami secara baik latarbelakang atau sejarah konflik perang saudara di wilayah ini sehingga mereka menulis berita tanpa memperhitungkan akibat lanjut dari pemberitaan tersebut.
Patut diakui bahwa banyak wartawan dari mancanegara dan juga datang dari wilayah lain di Indonesia menulis berita tentang konflik di Timor Timur. Mereka mungkin menulis berita secara benar namun sebuah kebenaran tidak harus selalu diungkapkan secara terbuka melalui media massa. Apalagi mayoritas masyarakat Timor Timur berpendidikan rendah yang sangat sulit memahami secara baik sebuah pemberitaan di media massa. Masyarakat sering menanggapi suatu persoalan atau sebuah berita secara emosional tanpa banyak menggunakan akal sehat. Masyarakat mudah terhasut dengan berbagai pemberitaan media massa yang bermuara pada pertikaian fisik.
Satu hal yang menakutkan adalah, para wartawan yang berdatangan dari berbagai negara itu setelah bertugas di Timor Timur langsung kembali ke negara mereka masing-masing namun kami sebagai wartawan lokal tetap tinggal di Timor Timur.Dampak dari berita yang ditulis rekan-rekan wartawan dari luar Timor Timur justeru dialami oleh wartawan lokal.Kemarahan masyarakat atas sebuah pemberitaan yang ditulis wartawan luar negeri dilampiaskan kepada wartawan yang tinggal di Timor Timur.
Berdasarkan trauma itulah maka, saya sendiri sering merasa sangat takut dan khawatir kalau melihat para wartawan yang datang dari luar negeri atau dari daerah lain di Indonesia melakukan tugas jurnalistik di wilayah perbatasan antarnegara Indonesia dengan Timor Timur. Saya khawatir jangan sampai mereka membuat berita bias yang bermuara pada konflik baru di wilayah perbatasan. Muara dari semuanya itu adalah wartawan lokal pun akan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa tidak puas atas sebuah berita yang bias.
Pengalaman di daerah rawan konflik Atambua
(Perbatasan dengan Timor Timur)
Pada 6 September 2000, tiga staf Kantor Perwakilan UNHCR di Atambua dibunuh sekelompok pengungsi Timor Timur pro-integrasi secara sangat mengenaskan. Setelah mereka membunuh, tiga jenasah itu dibakar di pekarangan Kantor perwakilan tersebut.
Saya menyaksikan betapa mengerikan proses pembakaran mayat-mayat itu. Walaupun masih menggelepar, tapi api terus membakar tubuh tiga korban keganasan para milisi itu. Beberapa staf UNHCR terpaksa melarikan diri dan bersembunyi di rumah kediaman Uskup Atambua Mgr Anton Pain Ratu,SVD yang berjarak sekitar 600 meter dari kantor UNHCR tersebut.
Salah seorang milisi yang memegang senjata api dengan sangat ganas secara mendadak menghadangku ketika sedang berjalan dari kediaman Uskup Atambua menuju kantor perwakilan UNHCR yang sedang terbakar. Milisi itu mengancam akan menghabisi nyawaku jika tidak memberitahu keberadaan Kepala Perwakilan UNHCR asal Malaysia itu.
Dengan penuh ketakutan saya memeluknya dan berkata:”Yang menjadi korban pengungsian ini bukan hanya kamu tetapi juga saya. Saya pun kehilangan segala-galannya di Timor Timur kecuali istri dan anakku yang masih hidup ketika harus mengungsi dari Timor Timur. Dan yang salah bukannya Kepala Perwakilan UNHCR itu. Dia hanya melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Jika kamu marah, jangan tumpahkan kemarahan itu kepada saya sebagai wartawan dan petugas UNHCR itu. Kini kita semua adalah korban,”.
Mendengar apa yang saya katakan itu, milisi yang sedang beringas itu kembali memeluk diriku dan menangis karena dia mengira tragedy Timor Timur yang disusul pengungsiannya ke Timor Barat disebabkan oleh UNHCR yang nota bene ketika itu banyak mempekerjakan orang-orang dari Barat. Milisi itu menuding lepasnya Timor Timur dari Indonesia akibat permainan politik Bangsa Barat. Menurut milisi itu, akibat permainan politik Bangsa Barat, dirinya bersama keluarga harus mengungsi dan kehilangan harta benda di Timor Timur. Dia sangat trauma dan membenci siapa saja yang berkulit putih berasal dari Barat.
Setelah insiden di Kantor Perwakilan UNHCR Atambua, masih begitu banyak insiden kemanusiaan yang terjadi di berbagai kamp pengungsian yang dibangun di hampir seluruh wilayah Kabupaten Belu, perbatasan dengan Timor Leste. Insiden pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM),baik dilakukan oleh milisi, oknum tertentu maupun kekerasan dalam rumah tangga para pengungsi yang hingga hari ini tetap bertahan tinggal di daerah perbatasan.
Saya mengalami dilema dalam menjalankan tugas jurnalistik yakni antara harus memberitakan semua pelanggaran HAM itu secara benar, adil dan transparan atau memikul akibat/resiko dari pemberitaan tersebut antara lain: mungkin diriku menjadi korban atau istri dan anakku menjadi korban kekerasan.
Banyak contoh kekerasan dan pengalaman traumatic bekeja di daerah rawan konflik yang jika diungkapkan hari ini, tentu akan membawa resiko kemanusiaan yang yang sangat krusial yang dapat bermuara pada kematian yang sangat tragis.
Untuk menceriterakan hal ini, saya membutuhkan waktu khusus. Kali ini, saya belum dapat mengungkapkan semua pengalaman traumatic di daerah perbatasan secara transparan karena “saya masih menjalani kehidupan bersama keluarga di wilayah rawan konflik itu”. “Aku,istri dan anakku masih ada, hari ini dan di sini!” Aku masih mempunyai anak yang dapat melanjutkan semangat dan karya ayahnya.
Mungkin, saya masih bisa cukup berani menceriterakan pengalaman kekerasan dan traumatic ketika bertugas di Timor Leste pada beberapa tahun yang silam (1992-1999) karena semua itu sudah merupakan “masa lalu” dan telah menjadi sebuah “sejarah kehidupan” yang tinggal dibukukan atau dibuatkan film untuk ditayangkan kepada generasi mendatang.
Bagiku, resiko mengisahkan sejarah kehidupan masa lalu, tentu lebih kecil jika dibandingkan dengan membuka aib kehidupan hari ini di sebuah daerah rawan konfilk ketika semua orang masih menjadi “saksi bisu sebuah drama kehidupan anak manusia” dan masih menjadi “kaum periferi yang tak bersuara”.
Nah,sampai di sini dulu kisah kehidupanku. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Semoga Tuhan masih mengaruniakan RAKHMAT KEHIDUPAN bagi kita semua untuk bersamaNya “meluruskan jalan yang bengkok”.
Bagaimanapun juga, dalam iman yang teguh, kita percaya bahwa Tuhan, Pemberi dan Penyelenggara kehidupan, tetap setia menulis lurus di atas garis kehidupan yang bengkok.
“ALLAH yang telah memulai karyaNya yang agung di dalam diri kita, akan meneruskan dan menyelesaikannya juga”.